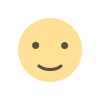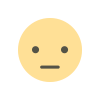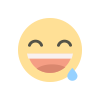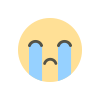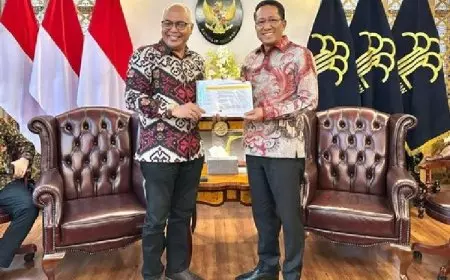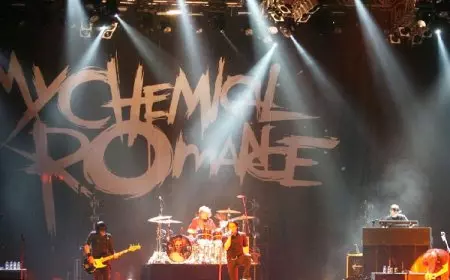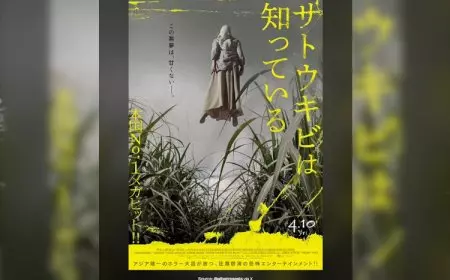Menikah Makin Langka di Indonesia: Data Bicara, Nilai Sosial Bergeser
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kompas.com menunjukkan sebuah realitas sosial yang tak bisa diabaikan: pernikahan di Indonesia kian jarang terjadi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakh

MALANG Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kompas.com menunjukkan sebuah realitas sosial yang tak bisa diabaikan: pernikahan di Indonesia kian jarang terjadi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah pernikahan nasional terus mengalami penurunan signifikan.
Jika pada 2014 tercatat lebih dari 2,1 juta peristiwa pernikahan, maka pada 2024 angkanya merosot menjadi sekitar 1,47 juta. Artinya, dalam satu dekade Indonesia kehilangan lebih dari 630 ribu pernikahan per tahun. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin perubahan besar dalam cara generasi muda memandang institusi pernikahan.
Tren penurunan tersebut sebenarnya mulai terlihat sejak pertengahan dekade lalu. Setelah sempat fluktuatif pada 2017 dan 2018, jumlah pernikahan kembali turun dan semakin tajam sejak 2020, bertepatan dengan pandemi Covid-19. Namun, ketika pandemi berlalu, angka pernikahan tak kunjung pulih. Sebaliknya, tren penurunan justru berlanjut hingga 2024. Fakta ini menandakan bahwa persoalan menikah bukan hanya soal situasi krisis sementara, melainkan berkaitan erat dengan perubahan nilai, prioritas hidup, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda.
Di satu sisi, penurunan angka pernikahan sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Biaya hidup yang kian tinggi, ketidakpastian pekerjaan, serta keinginan membangun karier lebih dahulu membuat banyak anak muda menunda atau bahkan mempertanyakan urgensi pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus segera dipenuhi setelah dewasa, melainkan sebagai pilihan hidup yang membutuhkan perhitungan matang.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI https://unisma.ac.id/
Namun, di sisi lain, fenomena ini menghadirkan paradoks. Ketika angka pernikahan secara resmi menurun, praktik nikah muda dan nikah siri justru masih ditemukan di berbagai daerah. Nikah muda, khususnya yang melibatkan dispensasi kawin, tetap terjadi dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, atau faktor ekonomi. Sementara itu, nikah siri muncul sebagai jalan pintas bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala usia, biaya, atau prosedur administratif. Artinya, penurunan angka pernikahan resmi tidak selalu berarti berkurangnya relasi perkawinan, melainkan bisa jadi pergeseran ke praktik-praktik yang berada di luar sistem pencatatan negara.
Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam dinamika sosial saat ini. Di perkotaan dan kelompok menengah, generasi muda cenderung menunda menikah, bahkan memilih hidup melajang lebih lama. Sementara di wilayah tertentu, pernikahan—termasuk pernikahan usia muda—masih dipandang sebagai solusi sosial atas berbagai persoalan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa penurunan angka pernikahan tidak berlangsung secara merata, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ekonomi, dan budaya.
Pergeseran nilai generasi muda juga turut memainkan peran besar. Narasi tentang kebebasan personal, kemandirian, dan pencapaian diri semakin dominan di ruang publik dan media sosial. Pernikahan tidak lagi menjadi tolok ukur utama kedewasaan atau kesuksesan hidup. Bahkan, dalam beberapa wacana populer, menikah di usia muda kerap dipandang sebagai keputusan terburu-buru yang berisiko menghambat pengembangan diri. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga memproduksi narasi tandingan berupa romantisasi nikah muda dan kehidupan rumah tangga ideal, yang kerap mengabaikan realitas tanggung jawab jangka panjang.
Dalam konteks ini, nikah siri menjadi fenomena yang patut dicermati secara kritis. Ketika negara memperketat aturan pernikahan dan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, sebagian pasangan memilih jalur informal demi memenuhi kebutuhan sosial atau religius. Padahal, praktik ini berisiko menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan secara hukum dan sosial. Ironisnya, di tengah menurunnya angka pernikahan resmi, praktik nikah siri justru bisa menjadi “angka gelap” yang luput dari statistik.
Penurunan angka pernikahan sejatinya tidak bisa dibaca secara hitam-putih sebagai kemajuan atau kemunduran. Di satu sisi, hal ini bisa mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapan menikah. Namun di sisi lain, tanpa diiringi kebijakan perlindungan sosial dan edukasi yang memadai, tren ini berpotensi mendorong munculnya praktik-praktik tidak aman seperti nikah siri atau pernikahan dini yang dipaksakan.
Data BPS seharusnya menjadi alarm bagi negara untuk membaca ulang dinamika sosial generasi muda. Pernikahan bukan semata urusan privat, tetapi berkaitan erat dengan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, dan stabilitas sosial. Ketika menikah makin langka, negara perlu memastikan bahwa pilihan menunda menikah benar-benar didukung oleh sistem pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial yang kuat—bukan justru mendorong masyarakat mencari jalan pintas di luar hukum.
Pada akhirnya, perubahan pola pernikahan adalah bagian dari transformasi sosial yang tak terelakkan. Tantangannya bukan sekadar menaikkan kembali angka pernikahan, melainkan memastikan bahwa setiap pilihan—baik menikah muda, menunda menikah, atau tidak menikah sama sekali—dilakukan secara sadar, aman, dan bertanggung jawab. Tanpa itu, penurunan angka pernikahan hanya akan menyembunyikan persoalan yang lebih dalam di balik statistik.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI https://unisma.ac.id/
*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?