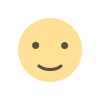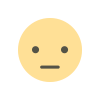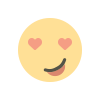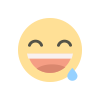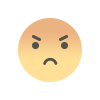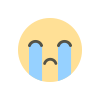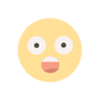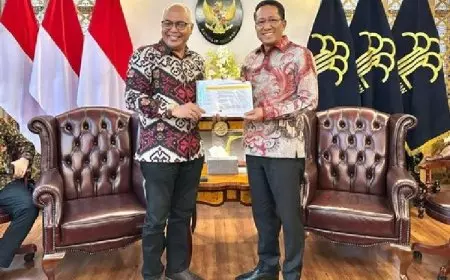Ekologi yang Feminin: Mengapa Konservasi Tak Bisa Tanpa Perempuan?
Ketika laut kian menelan daratan, perempuan di pesisir Indonesia justru menanam harapan. Di saat abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim mengancam, tangan-tangan mereka menjadi benteng ter

JAKARTA Ketika laut kian menelan daratan, perempuan di pesisir Indonesia justru menanam harapan. Di saat abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim mengancam, tangan-tangan mereka menjadi benteng terakhir yang menahan laju kehancuran ekologi. Fenomena ini bukan sekadar gambaran ketangguhan gender, melainkan cermin dari relasi etis antara manusia dan alam yang kini kian langka dalam paradigma pembangunan modern. Dalam kepedulian dan kerja sunyi perempuan pesisir, kita melihat bentuk lain dari keberlanjutan yang tidak hanya bertumpu pada logika dominasi, tetapi pada empati, keseimbangan, dan tanggung jawab antargenerasi.
Namun di balik peran besar itu, wacana pembangunan masih menempatkan perempuan sebagai subjek sekunder berupa pelengkap narasi dan bukan pusat perubahan. Padahal, perempuan pesisir adalah pihak yang paling terdampak sekaligus paling berdaya dalam menghadapi krisis ekologis. Mereka menjaga hutan mangrove, mengelola hasil laut, dan menopang ekonomi keluarga, tetapi jarang diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketimpangan ini menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan gender berupa degradasi ekologis dan marginalisasi perempuan yang sesungguhnya adalah dua sisi dari sistem yang sama.
Pada konteks perubahan iklim, peran perempuan bukan sekadar adaptif tetapi juga transformatif. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri terhadap dampak, melainkan menciptakan inovasi sosial dan ekonomi yang mendukung ketahanan komunitas. Dari menanam mangrove hingga mengembangkan ekowisata berbasis komunitas, perempuan membangun model ekonomi sirkular yang mengutamakan keberlanjutan.
Akan tetapi upaya ini sering kali berjalan tanpa dukungan memadai dari negara atau institusi. Pelibatan perempuan masih dianggap sebagai "isu tambahan," bukan komponen inti dari kebijakan lingkungan. Padahal, keberhasilan konservasi di tingkat lokal menunjukkan bahwa inklusivitas gender adalah prasyarat bagi efektivitas ekologis.
Indonesia, dengan 3,31 juta hektare hutan mangrove — yang sebagian besar kini kritis akibat industrialisasi pesisir — memiliki potensi besar untuk membangun konservasi berbasis komunitas. Namun, selama kebijakan masih terpusat pada pendekatan teknokratis, keberhasilan itu akan sulit dicapai.
Perempuan yang selama ini menjadi penjaga ekosistem tidak cukup hanya diakui, tetapi harus diberdayakan secara struktural. Artinya, mereka harus terlibat dalam perencanaan, mendapatkan akses terhadap modal, pendidikan, dan posisi strategis dalam tata kelola lingkungan. Pelibatan perempuan bukan hanya persoalan moralitas, tetapi strategi ekologis yang terbukti efektif, sebagaimana ditunjukkan penelitian CIFOR–UNDP (2023) dan UN Women (2022).
Karena itu, membangun paradigma ekologi yang feminin berarti menata ulang cara kita memahami pembangunan. Ia menggeser fokus dari dominasi menjadi kolaborasi, dari pertumbuhan menuju keberlanjutan, dari eksploitasi menuju perawatan. Ekologi feminin bukan tentang kelembutan yang lemah, melainkan tentang kekuatan yang hidup dari empati dan tanggung jawab terhadap kehidupan. Ketika perempuan di pesisir menanam mangrove di tengah naiknya air laut, sesungguhnya mereka sedang menanam masa depan — bukan hanya bagi komunitasnya, tetapi bagi peradaban yang lebih adil secara ekologis. Dan mungkin, dalam akar-akar mangrove yang mereka rawat, tersimpan jawaban atas krisis planet yang kita hadapi hari ini.
Kisah dari Lapangan: Dari Bedono hingga Teluk Bintuni
Kisah dari lapangan memperkuat kesimpulan tersebut. Di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah, perempuan nelayan membentuk “Sekolah Lapang Pesisir” dengan dukungan LSM dan universitas. Program ini memadukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal rewang—tradisi gotong royong perempuan Jawa yang mengutamakan kebersamaan dan saling bantu. Mereka bukan hanya menanam ribuan bibit mangrove, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi desa melalui ekowisata berbasis komunitas. Berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun (2023), tingkat abrasi di pesisir Bedono menurun hingga 40 persen sejak program tersebut dijalankan secara partisipatif.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, muncul kelompok “Srikandi Mangrove” yang mengolah buah mangrove menjadi sirup, dodol, dan batik berpewarna alami. Melalui inovasi ini, perempuan tak hanya berperan dalam konservasi, tetapi juga membangun ekonomi hijau berbasis sumber daya lokal. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur (2023) menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga anggota kelompok ini meningkat rata-rata 25–30 persen per bulan tanpa menambah tekanan terhadap lingkungan. Banyuwangi kini dikenal sebagai salah satu kabupaten pionir green economy berbasis perempuan pesisir.
Di Sulawesi Selatan, perempuan Bugis mempertahankan kearifan “Pattuppu Tanah”, larangan adat menebang mangrove secara sembarangan karena dianggap mengundang murka laut. Tradisi ini menjadi bentuk local law enforcement yang berfungsi jauh sebelum hukum konservasi modern hadir. Riset Universitas Hasanuddin (2022) menunjukkan bahwa wilayah yang masih memegang teguh nilai ini memiliki tutupan mangrove 15–20 persen lebih tinggi dibanding desa yang telah meninggalkan adat tersebut.
Lebih ke timur, di Teluk Bintuni, Papua Barat, kelompok perempuan Arfak menerapkan prinsip igya ser hanjop—“berdiri menjaga batas”—sebagai dasar pengelolaan hutan mangrove. Mereka menanam lebih dari 300 ribu bibit sejak 2021 dan menjadikan konservasi sebagai praktik spiritual sekaligus ekonomi. Kolaborasi mereka dengan pemerintah daerah dan sektor swasta menjadikan Teluk Bintuni model community-based blue carbon initiative di Indonesia Timur.
Contoh-contoh ini menegaskan bahwa konservasi yang berhasil selalu berakar pada masyarakat, terutama ketika nilai-nilai lokal dihidupkan oleh perempuan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan prinsip inclusiveness dan local empowerment yang menjadi roh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Namun, sistem pembangunan yang masih maskulin sering gagal melihat potensi ini. Pendekatan teknokratis dan terpusat menempatkan alam sebagai objek yang bisa direkayasa, bukan subjek yang harus dihormati. Padahal, ekologi feminin mengajarkan bahwa menjaga alam berarti menjalin relasi etis dengannya. Perempuan pesisir memahami bahwa mangrove bukan sekadar pohon, tetapi sistem kehidupan yang menyatukan laut, darat, dan manusia. Pengetahuan ini bersifat relasional—diperoleh melalui pengalaman harian, bukan hanya data ilmiah.
Sayangnya, kebijakan nasional masih cenderung abai terhadap pengetahuan lokal tersebut. Dari 90 proyek konservasi pesisir dalam Rencana Aksi Nasional Mangrove (KLHK, 2023), hanya 18 persen yang secara eksplisit mencantumkan pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pemberdayaan gender dan praktik nyata di lapangan. Hambatan terbesar bukan pada ketidakmampuan perempuan, tetapi pada struktur sosial yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Data BPS (2024) mencatat hanya 41 persen perempuan pesisir yang menamatkan pendidikan menengah. Rendahnya akses pendidikan membatasi peluang mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, beban ganda—mengurus keluarga sekaligus mencari nafkah—membuat ruang partisipasi publik semakin sempit.
Karena itu, pemberdayaan perempuan dalam konservasi tidak bisa berhenti pada pelatihan teknis menanam mangrove atau membuat produk olahan. Ia harus disertai transformasi sosial berupa pengakuan terhadap hak perempuan atas sumber daya alam, akses pada pendanaan dan pendidikan, serta ruang politik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konservasi menjadi sarana pembebasan, bukan sekadar kerja tambahan yang menambah beban gender.
Ekologi yang feminin adalah antitesis dari model pembangunan eksploitatif yang selama ini mendominasi. Dalam logika pembangunan konvensional, alam dilihat sebagai sumber daya yang harus diolah demi pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam logika feminin, alam adalah mitra yang harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan. Perempuan pesisir memahami hal ini melalui praktik keseharian—mereka tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali.
Konsep ini sejalan dengan pemikiran ekofeminisme, yang menyoroti keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Vandana Shiva, tokoh ekofeminisme asal India, berargumen bahwa krisis ekologi adalah cerminan dari sistem patriarki yang mengagungkan kontrol dan dominasi. Bagi Shiva, solusi ekologis tidak mungkin dicapai tanpa keadilan gender, karena cara pandang terhadap perempuan dan alam berasal dari akar yang sama, yakni keduanya dianggap dapat dieksploitasi tanpa batas.
Pada konteks Indonesia, ekofeminisme menemukan bentuk khasnya. Tradisi seperti rewang, pattuppu tanah, dan igya ser hanjop memperlihatkan bahwa hubungan manusia dan alam bersifat komunal dan spiritual, bukan transaksional. Di balik tradisi tersebut, perempuan memainkan peran penting sebagai penjaga nilai-nilai ekologis. Dengan kata lain, keberlanjutan ekologis Indonesia bertumpu pada keberlanjutan kultural yang dijaga perempuan.
Kearifan Lokal dalam Fondasi Konservasi Modern
Dari perspektif ekonomi hijau, peran perempuan juga semakin relevan. Bank Dunia (2023) mencatat bahwa proyek restorasi mangrove dengan keterlibatan komunitas perempuan memiliki tingkat keberlanjutan lebih dari 80 persen dalam tiga tahun, dibanding hanya 60 persen pada proyek yang dikelola secara top-down. Hal ini disebabkan karena perempuan cenderung memprioritaskan kesejahteraan kolektif dibanding keuntungan individual, serta mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya.
Pada kerangka SDGs, keterlibatan perempuan dalam konservasi mendukung setidaknya empat tujuan, yaitu Gender Equality (SDG 5), Life Below Water (SDG 14), Life on Land (SDG 15), dan Climate Action (SDG 13). Keempatnya saling terkait dalam upaya membangun masa depan berkelanjutan. Ketika perempuan berdaya, alam terlindungi; ketika alam lestari, komunitas menjadi tangguh terhadap perubahan iklim.
Di sinilah esensi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi menciptakan harmoni sosial-ekologis. Partisipasi perempuan dalam konservasi tidak sekadar memenuhi indikator gender mainstreaming, tetapi memperkuat ketahanan sosial terhadap bencana ekologis. Dalam situasi krisis iklim yang kian nyata, logika pembangunan yang berorientasi pada kompetisi dan eksploitasi perlu digantikan dengan logika kolaborasi dan perawatan—logika yang telah lama dipraktikkan oleh perempuan pesisir.
Meski demikian, mengarusutamakan ekologi feminin dalam kebijakan nasional masih membutuhkan keberanian politik dan perubahan paradigma. Pemerintah perlu menjadikan pengetahuan lokal perempuan sebagai dasar desain kebijakan, bukan hanya pelengkap laporan proyek. Pendekatan partisipatif harus diinstitusionalisasi sejak tahap perencanaan, bukan sekadar formalitas dalam pelaksanaan. Selain itu, mekanisme pendanaan konservasi seperti blue carbon credit dan payment for ecosystem services harus menyediakan skema khusus bagi kelompok perempuan agar mereka memperoleh manfaat ekonomi secara adil.
Lembaga pendidikan dan riset juga memiliki peran penting dalam memperkuat ekologi feminin. Kurikulum pengelolaan sumber daya alam harus memasukkan perspektif gender dan kearifan lokal, bukan sekadar pendekatan bioteknis. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan ilmu ekologi, antropologi, dan gender studies perlu diperluas agar mampu menangkap kompleksitas hubungan manusia–alam secara utuh.
Selain itu, media memiliki tanggung jawab moral untuk menarasikan perempuan sebagai subjek perubahan, bukan korban. Representasi perempuan pesisir yang berjuang menanam mangrove, mengelola limbah, atau mendidik generasi muda tentang ekologi harus diangkat sebagai bagian dari identitas pembangunan Indonesia. Hanya dengan cara itu, wajah konservasi nasional dapat berubah menjadi lebih manusiawi dan inklusif.
Dari Akar Mangrove ke Akar Perubahan
Ekologi yang feminin bukanlah tentang kelembutan yang pasif, melainkan tentang kekuatan yang tumbuh dari kepedulian dan ketekunan dalam merawat kehidupan. Seperti akar mangrove yang menembus lumpur, perempuan pesisir telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati justru lahir dari kesabaran dan keberlanjutan. Mereka menanam bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan; menjaga bukan karena diperintah, tetapi karena mencintai. Dalam tindakan kecil yang berulang, seperti menanam, merawat, dan berbagi manfaat, mereka menegaskan bahwa konservasi sejati berakar pada kasih dan tanggung jawab, bukan pada wacana besar atau proyek sementara.
Dari akar yang menjalar di lumpur pesisir, tumbuhlah akar kesadaran baru bahwa pelibatan perempuan dalam konservasi bukanlah bentuk belas kasih, tetapi kebutuhan strategis di tengah krisis iklim. Mereka bukan sekadar pelaku lapangan, melainkan penjaga nilai-nilai yang menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika kebijakan sering berbicara dalam angka, perempuan menghadirkan wajah kemanusiaan dalam pembangunan. Di tangan mereka, konservasi menjadi praktik hidup yang menghubungkan ekonomi, budaya, dan spiritualitas yang menjadikan pelestarian alam bukan sekadar kerja teknis, tetapi juga gerakan moral.
Jika konservasi adalah upaya menjaga masa depan, maka perempuanlah yang kini berdiri di garda terdepan untuk menjaganya. Di sepanjang garis pantai Indonesia, dari Bedono hingga Teluk Bintuni, mereka menulis bab baru tentang keberlanjutan dengan lumpur di kaki dan harapan di hati. Namun perjuangan ini hanya akan bermakna jika negara, akademisi, dan masyarakat memberi ruang yang adil bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan. Sebab, masa depan bumi tidak akan bertahan di atas sistem yang masih menyingkirkan setengah dari kekuatan penjaganya.
Akar mangrove yang kuat adalah simbol dari kekuatan perempuan Indonesia yang menopang kehidupan, menahan badai, dan memastikan bumi tetap bernafas. Dari akar-akar itulah seharusnya pembangunan kita bertumbuh dari bawah, dari komunitas, dari nilai-nilai kasih dan kearifan lokal. Karena hanya dengan mengakui perempuan sebagai inti dari ekologi dan pembangunan, kita bisa membangun masa depan yang benar-benar berakar yang tidak hanya di tanah, tetapi juga di nurani kemanusiaan.
Sumber Data: KLHK (2024); BPS (2024); CIFOR–UNDP (2023); UN Women (2022); World Bank (2023); DKP Jawa Timur (2023); Universitas Hasanuddin (2022); Balai DAS Pemali Jratun (2023).
***
*) Oleh: Prima Yustitia Nurul Islami, Mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?