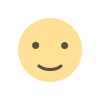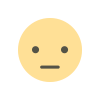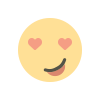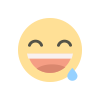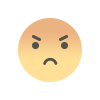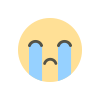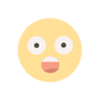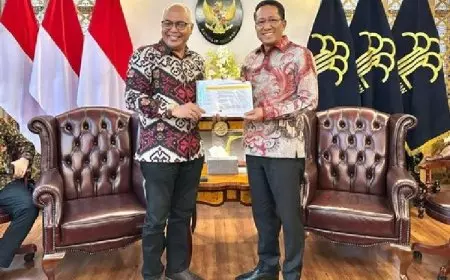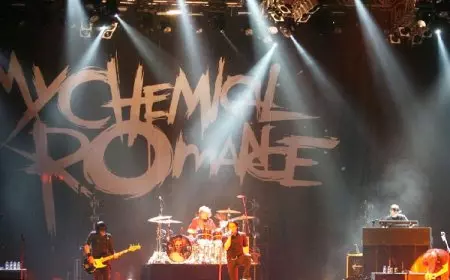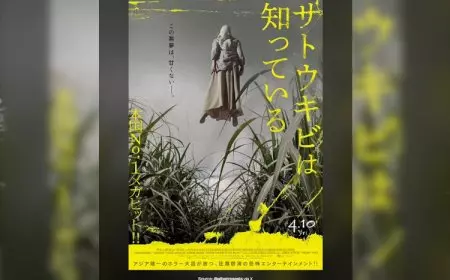Ketika Logika Pasar Gagal Membaca Logika Makna
Tayangan Trans7 tentang kehidupan pesantren baru-baru ini bukan sekadar miskomunikasi redaksional, melainkan contoh salah paham epistemik.

Tayangan Trans7 tentang kehidupan pesantren baru-baru ini bukan sekadar miskomunikasi redaksional, melainkan contoh salah paham epistemik. Kamera media, yang dikuasai logika visual dan sensasional, mencoba merekam dunia yang hidup dengan ritme batin dan spiritual yang berbeda. Dunia pesantren bukan sekadar drama sosial yang bisa ditangkap oleh lensa; ia adalah ekosistem moral dan simbolik yang bergerak dengan logika makna, bukan logika pasar. Dari sinilah kesalahan mendasar muncul: media menilai pesantren dengan kategori ekonomi modern, bukan dengan pemahaman budaya yang mendalam.
Logika Makna Pesantren vs Logika Pasar
Bagi dunia industri, semua aktivitas harus bisa diukur, dikalkulasi, dan dipertukarkan dalam istilah modal. Namun pesantren hidup dengan logika yang berbeda. Pengabdian (khidmah) tidak diukur dengan honorarium, dan keberkahan (barokah) tidak dihitung dengan angka. Dalam tayangan Trans7, santri yang membantu di dapur atau membersihkan masjid dianggap sebagai “tenaga kerja”, sementara kiai yang tampak sejahtera ditafsir sebagai “pemodal utama”. Cara pandang ini simplistik sekaligus menyesatkan, karena menilai dunia pesantren dengan standar yang asing bagi kebudayaan itu sendiri.
Dunia Pesantren dan Cultural Logic
Dalam antropologi, setiap komunitas memiliki cultural logic, atau logika budaya yang menjelaskan mengapa suatu tindakan dianggap benar, pantas, dan terhormat. Dunia pesantren bekerja dalam logika spiritual dan simbolik. Khidmah bukan kerja paksa, tetapi laku spiritual; barokah adalah modal utama, bukan uang; relasi kiai-santri bukan hubungan ekonomi, melainkan hubungan genealogis-ruhaniyah, seperti antara ayah dan anak. Menafsirkan khidmah santri sebagai eksploitasi adalah contoh nyata dari benturan epistemik: simbol budaya dibaca dengan bahasa ekonomi.
Relasi Kiai–Santri: Transformasi Moral
Clifford Geertz dalam The Religion of Java menegaskan bahwa hubungan kiai dan santri bersifat paternalistik sekaligus edukatif. Santri belajar melalui teladan dan pelayanan, bukan hanya melalui pengajaran formal. Mereka mencuci piring, menyapu halaman, atau menyambut tamu kiai bukan karena diperintah, tetapi sebagai laku pengendalian diri dan proses pembelajaran moral. Menyebut hubungan ini sebagai feodalisme adalah kesalahan konseptual: hierarki di pesantren bukan bentuk dominasi, tapi metode pendidikan karakter. Media yang membaca hal ini dengan lensa modern gagal memahami transformasi moral yang tengah berlangsung.
Ekonomi Simbolik Pesantren
Dalam perspektif antropologi ekonomi, pertukaran di pesantren bersifat simbolik, bukan materialistik. Marcel Mauss, dalam karyanya The Gift, menunjukkan bahwa tidak semua pemberian dan pelayanan di masyarakat bersifat transaksi ekonomi. Santri yang membantu pondok sebagai balasan atas ilmu yang diterima sebenarnya menjalankan reciprocity atau timbal balik simbolik. Mereka tidak menerima gaji, tetapi keberkahan, ilmu, dan doa—bentuk modal sosial dan spiritual yang lebih berharga daripada uang. Menafsirkan hubungan ini dengan istilah “upah” atau “eksploitasi” adalah salah kerangka budaya.
Kekuasaan Simbolik Kiai
Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai modal simbolik, yaitu kekuasaan yang lahir dari integritas moral dan legitimasi sosial. Kiai memperoleh pengaruh bukan karena harta, tetapi karena keilmuan, akhlak, dan penghormatan yang diberikan masyarakat. Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren juga mencatat bahwa banyak kiai justru menghidupi santri, membangun madrasah, dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan kiai sering kali berputar kembali kepada umat. Namun kamera media, yang haus sensasi, sering hanya menyorot apa yang tampak secara material, bukan makna yang memuliakan.
Framing Media dan Kegagalan Cultural Translation
Kesalahan terbesar Trans7 ada pada framing media itu sendiri. Dalam antropologi media, setiap tayangan bukan sekadar laporan realitas, tetapi konstruksi naratif. Narasi yang dihasilkan oleh Trans7 jelas menggunakan logika modern-rasional-materialistik. Mereka gagal melakukan cultural translation, yakni menerjemahkan nilai budaya pesantren ke dalam bahasa yang adil, proporsional, dan akurat. Tugas jurnalisme sejati menuntut emic understanding: pemahaman dari dalam sistem budaya itu sendiri. Tanpa perspektif ini, tradisi luhur direduksi menjadi tontonan, pengabdian suci dianggap perbudakan, dan masyarakat hanya melihat “drama visual” tanpa menangkap makna yang sebenarnya.
Kamera vs Cermin: Pesantren Memantulkan Makna
Dunia pesantren punya cermin, bukan kamera. Kamera menangkap permukaan; cermin menyingkap kedalaman. Kamera merekam fakta; cermin memantulkan kesadaran. Di pesantren, cermin itu adalah batin santri—tempat introspeksi, pengendalian diri, dan pembelajaran keikhlasan. Karena itu, pesantren tidak menolak liputan media, tapi menolak reduksi makna. Sorot kamera boleh hadir, tapi harus sejalan dengan pemahaman budaya yang benar.
Kesimpulan: Pesantren sebagai Guru Moral Bangsa
Pesantren tidak sedang berkompetisi dengan media. Ia hanya ingin diwartakan secara jujur, bukan dipersingkat menjadi stereotipe sensasional. Jika media terus membaca logika makna dengan kacamata logika pasar, publik akan kehilangan pemahaman yang tepat, dan pesantren hanya akan terlihat sebagai institusi eksotik atau problematis. Kekuatannya ada pada kesederhanaan, keikhlasan, dan ketulusan moral yang tumbuh dari praktik sehari-hari—nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan angka atau upah. Media boleh menguasai teknologi dan lensa, tetapi pesantren mengajarkan cara menguasai diri dan hati.
***
*) Oleh: Oleh: Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.
Apa Reaksi Anda?