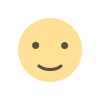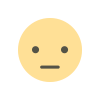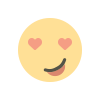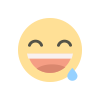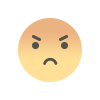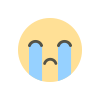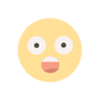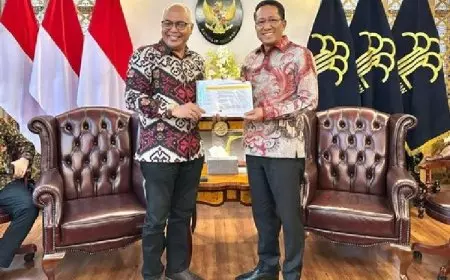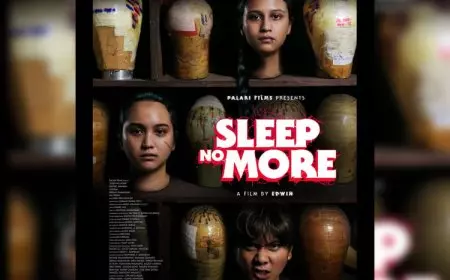Pesantren, Benteng Keluarga Maslahah di Tengah Generasi Fatherless
Fenomena fatherless generation atau generasi tanpa figur ayah saat ini tengah menjadi sorotan penting dengan banyaknya perceraian pasangan suami istri.

Fenomena fatherless generation atau generasi tanpa figur ayah saat ini tengah menjadi sorotan penting dengan banyaknya perceraian pasangan suami istri. Data Susenas 2024 memperkirakan bahwa sekitar 15,9 juta anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik maupun emosional, sehingga dalam kurun waktu yang sayang dekat terdapat angka mencengangkan dan menjadi potret rapuhnya fondasi keluarga modern secara sistematis.
Kondisi ini bukan sekadar masalah sosial, tetapi krisis nilai yang merambah ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bangsa. Dalam situasi ini, pesantren muncul bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng terakhir yang menjaga keutuhan moral dan adab generasi muda.
Fenomena fatherless di Indonesia memiliki banyak komplikasi dan sebab akibatnya. Fenomena ini lahir dari perceraian, migrasi ekonomi, hingga disfungsi keluarga akibat ketidakhadiran emosional seorang ayah. Dampaknya juga tidak sederhana: anak kehilangan figur teladan, merasa hampa secara spiritual, dan mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar yang cenderung destruktif.
Dalam konteks inilah pesantren memainkan peran sosial yang lebih luas daripada sekadar tempat belajar kitab kuning. Pesantren menjadi ruang pengasuhan kolektif, di mana santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, lebih dari itu juga diasuh, dibimbing, dan diarahkan sebagaimana seorang ayah menuntun anaknya menuju kedewasaan moral.
Perlu dipahami juga bahwa Penelitian-penelitian terbaru dari berbagai universitas Islam negeri menegaskan fungsi vital pesantren dalam membentuk karakter sosial dan spiritual anak. Kajian dari UIN dan STAI pada 2024 menjadi satu dari banyak penelitian yang dilakukan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa pola hidup santri di bawah bimbingan kiai menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan keteguhan moral.
Di tengah generasi yang dibesarkan oleh gawai dan algoritma, pesantren tetap mempertahankan sistem pengasuhan berbasis ta’dib—pendidikan yang menempatkan adab di atas ilmu. Santri belajar bukan hanya bagaimana menjadi cerdas, tetapi juga bagaimana menjadi manusia yang beradab.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Sementara itu, studi fenomenologis terbaru mengungkap bahwa anak-anak dari keluarga fatherless mengalami kesulitan dalam mengenali figur otoritas yang sehat. Mereka cenderung mencari validasi dari luar, bahkan dari dunia digital yang penuh bias. Pesantren, dengan model interaksi yang berbasis kasih sayang dan keteladanan, mengisi kekosongan tersebut. Hubungan antara santri dan kiai bukan hanya relasi akademik, melainkan juga relasi emosional dan spiritual yang menyerupai relasi ayah-anak. Di sinilah pesantren menjadi oase di tengah kegersangan pengasuhan modern—tempat di mana cinta, kedisiplinan, dan keteladanan berpadu.
Lebih dari itu, konsep keluarga maslahah—keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat—menemukan bentuk praksisnya di pesantren. Lingkungan pesantren menciptakan ekosistem nilai yang menumbuhkan kepedulian sosial, ketaatan beragama, serta tanggung jawab terhadap sesama. Dalam konteks ini, pesantren bukan hanya benteng moral, tetapi juga laboratorium sosial yang menyiapkan generasi berjiwa pemimpin dan berkarakter. Ketika rumah tangga banyak yang kehilangan figur ayah, pesantren menghadirkan figur kolektif yang menuntun, menasihati, dan memeluk anak-anak bangsa dengan ketulusan.
Namun, peran besar pesantren tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan inovasi dan kesadaran zaman. Tantangan digitalisasi, derasnya arus budaya populer, dan melemahnya otoritas keagamaan menuntut pesantren untuk tetap adaptif. Para kiai dan pengasuh perlu memanfaatkan teknologi bukan untuk menyaingi dunia luar, tetapi untuk menanamkan nilai dengan cara yang lebih relevan bagi generasi digital. Nilai-nilai klasik seperti tawadhu’, ta’zim, dan ikhlas harus diterjemahkan ke dalam bahasa keseharian anak muda agar tidak kehilangan makna.
Kritik terhadap sistem pendidikan modern yang terlalu menekankan aspek kognitif dan mengabaikan pembentukan karakter menemukan jawabannya di pesantren. Di sana, belajar bukan sekadar menumpuk pengetahuan, tetapi melatih kesadaran dan mengasah nurani. Pesantren menolak dikotomi antara akal dan adab; keduanya harus berjalan beriringan agar ilmu menjadi berkah. Dengan demikian, keberadaan pesantren adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang kian individualistik dan kehilangan arah moral.
Pada akhirnya, benang merah dari semua ini terletak pada pentingnya menghidupkan kembali semangat pendidikan sebagai basis adab yang saat ini cenderung dianggap feudal. Pesantren telah membuktikan diri sebagai lembaga yang mampu menggantikan peran keluarga dalam mendidik generasi yang kehilangan sosok ayah. Di tengah laju zaman yang tidak menentu, pesantren tetap kokoh sebagai benteng keluarga maslahah menjaga nilai, kemudian membentuk karakter, dan bahkan juga mampu memelihara kemanusiaan. Ketika dunia sibuk memproduksi manusia agar menjadi pintar, pesantren dengan tenang melahirkan manusia beradab yang secara tidak sadar justru menjadi keunggulan. ***
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?