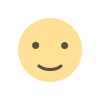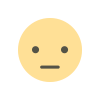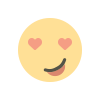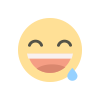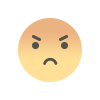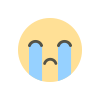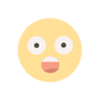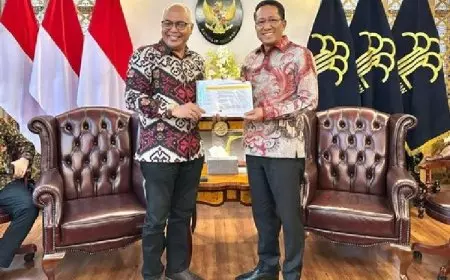Suhu Kota Kian Memanas: Peringatan Ilmiah di Balik Hilangnya Paru-Paru Hijau Kita
Bayangkan pagi hari di tengah kota yang belum sepenuhnya terjaga. Deru kendaraan mulai terdengar, langit yang seharusnya biru tertutup kabut tipis keabu-abuan, dan napas pertama yang Anda tarik bukan

JAKARTA Bayangkan pagi hari di tengah kota yang belum sepenuhnya terjaga. Deru kendaraan mulai terdengar, langit yang seharusnya biru tertutup kabut tipis keabu-abuan, dan napas pertama yang Anda tarik bukan udara segar, melainkan kepulan asap tipis bercampur debu. Di antara gedung-gedung tinggi yang seolah berlomba menembus awan, udara terasa lebih pekat, sinar matahari terasa lebih dekat, dan teduh menjadi barang langka. Begitulah wajah kota-kota kita hari ini—sesak, panas, dan rapuh terhadap bencana. Banyak orang menganggapnya sebagai risiko wajar dari kemajuan, seolah menjadi harga yang harus dibayar untuk status “metropolitan”. Namun di balik itu, sesungguhnya sedang berlangsung krisis ekologis yang dapat diukur dan ditelusuri, dari hilangnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru terakhir dari kehidupan urban.
Krisis ini bukan sekadar keluhan estetika tentang berkurangnya taman, melainkan ancaman eksistensial bagi kelayakan hidup manusia di kota. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi gambaran yang tidak main-main, yakni 55 persen populasi dunia kini tinggal di kawasan perkotaan, dan angka itu diproyeksikan melonjak menjadi 68 persen pada tahun 2050.
Dua dari tiga manusia di planet ini akan hidup di kota, dan bila kota-kota itu terus menyingkirkan ruang hijaunya, maka masa depan manusia akan dibangun di atas panas, polusi, dan banjir. Urbanisasi, yang semula menjadi simbol kemajuan, berpotensi berubah menjadi gerbang menuju kejatuhan ekologis.
Selama ini, ruang terbuka hijau atau RTH sering kita bayangkan sebatas taman, jalur hijau, atau lahan kosong di antara bangunan. Padahal, dalam pandangan ekologis, RTH adalah sistem penyangga kehidupan—life support system—yang bekerja dalam diam. Ia adalah “paru-paru” dan sekaligus “ginjal” kota yang menyaring udara, menstabilkan suhu, dan meresapkan air.
Pada tubuh kota, RTH adalah organ vital yang menentukan keseimbangan antara beton dan kehidupan. Namun pembangunan yang dikejar dengan logika profit telah mencabut organ vital itu satu demi satu, menjadikan kota bagai tubuh tanpa ventilasi.
Bukti Sains yang Mengejutkan: RTH Bukan Lagi Pilihan
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan standar minimal RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah kota. Angka ini bukan hasil kompromi politis, tetapi perhitungan ekologis agar kota tetap memiliki kapasitas serapan air, penyeimbang suhu, dan sirkulasi udara yang memadai. Namun, kenyataannya, di kota-kota besar Indonesia angka itu jarang terpenuhi. Jakarta, misalnya, hanya memiliki sekitar sembilan hingga sepuluh persen RTH dari total wilayahnya. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan peringatan dini tentang masa depan yang panas, pengap, dan tergenang. Ketika proporsi RTH menurun, suhu naik, udara kotor menumpuk, dan air kehilangan tempat untuk kembali ke tanah.
Secara ilmiah, pentingnya RTH tidak bisa ditawar. Dalam bahasa fisika, RTH adalah sistem pendingin alami raksasa. Efek Pulau Panas Perkotaan (Urban Heat Island) terjadi ketika material seperti beton, aspal, dan kaca—yang mendominasi lanskap kota—menyerap panas matahari di siang hari dan memancarkannya kembali di malam hari. Akibatnya, suhu kota bisa lima hingga sepuluh derajat lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
Perbedaan kecil ini membawa konsekuensi besar, yakni meningkatnya risiko heatstroke, kelelahan, hingga kematian akibat panas ekstrem. Di titik inilah pepohonan bekerja sebagai pendingin alami. Melalui proses evapotranspirasi, mereka melepaskan uap air ke udara, menurunkan suhu lingkungan, sekaligus menjaga kelembapan.
Citra satelit termal menunjukkan bahwa wilayah dengan tutupan pohon yang baik memiliki suhu permukaan hingga beberapa derajat lebih rendah dibandingkan area gersang di sekitarnya. RTH, dengan demikian, bukan ornamen kota, melainkan pendingin ekologis yang menghemat energi, mengurangi ketergantungan pada pendingin buatan, dan menekan emisi gas rumah kaca.
Selain menjadi pendingin, RTH adalah penyaring udara paling efektif yang pernah ditemukan. Setiap daun, setiap pori kulit batang, bekerja tanpa henti menjebak partikel polutan yang tak kasatmata: nitrogen oksida, sulfur oksida, dan partikulat halus (PM2.5) yang menjadi biang penyakit pernapasan dan jantung. Di saat industri dan kendaraan bermotor terus memuntahkan racun ke atmosfer, pohon-pohon di taman kota bekerja sebagai “masker raksasa” bagi seluruh warga.
Satu pohon dewasa mampu menyerap lebih dari 20 kilogram karbon dioksida per tahun dan melepaskan oksigen yang cukup untuk dua manusia bernapas. Maka ketika taman digusur untuk parkiran atau pusat perbelanjaan, sesungguhnya kita sedang menghapus alat penjernih udara kolektif yang tak tergantikan.
Tidak berhenti di udara, fungsi ekologis RTH merembes ke tanah dan air. Setiap akar pohon berperan sebagai pipa alami yang mengalirkan air hujan ke lapisan bawah bumi. Tanah yang gembur di bawah vegetasi berfungsi seperti spons besar yang menahan air sementara, mengurangi limpasan permukaan, dan mencegah banjir. Ketika lahan hijau berubah menjadi beton, air kehilangan jalannya untuk meresap, dan akhirnya meluap menjadi banjir yang menelan kota. Ironisnya, setiap kali banjir terjadi, kita menyalahkan drainase yang tersumbat, padahal akar masalahnya adalah hilangnya akar pohon.
Namun, RTH tidak hanya menyehatkan tubuh kota secara fisik. Ia juga menyembuhkan jiwa warganya. Psikologi lingkungan telah lama mengenal konsep biophilia—kecenderungan bawaan manusia untuk mencintai dan mencari kedekatan dengan alam. Sebuah studi menunjukkan bahwa berjalan di taman selama dua puluh menit dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan perasaan bahagia.
Pada masyarakat urban yang dicekam tekanan kerja dan kebisingan, ruang hijau menjadi oasis mental. Ia menyediakan tempat bermain bagi anak-anak, tempat berlari bagi pekerja yang lelah, dan tempat duduk hening bagi mereka yang mencari jeda dari kebisingan. RTH adalah ruang sosial paling egaliter: semua orang, tanpa memandang status, berhak menikmatinya. Taman adalah demokrasi ekologis dalam bentuk paling nyata.
Sayangnya, dalam logika ekonomi kota modern, lahan hijau sering dianggap tidak produktif. Di atas kertas, lahan kosong lebih menguntungkan jika diubah menjadi mal, apartemen, atau jalan tol. Investor menilai setiap meter persegi tanah dari potensi laba, bukan dari fungsi ekologisnya. Padahal, jika dihitung dengan jujur, kerugian ekonomi akibat rusaknya ekosistem jauh lebih besar. Banjir yang menenggelamkan rumah dan infrastruktur, polusi udara yang meningkatkan biaya kesehatan publik, hingga stres yang menurunkan produktivitas kerja—semuanya menimbulkan beban ekonomi yang tak terbayar oleh keuntungan jangka pendek pembangunan properti.
Berbagai penelitian mutakhir memperkuat peringatan ini. Studi Muladi et al. (2024) di Jurnal Ilmu Lingkungan menunjukkan bahwa penurunan rasio RTH di bawah 15 persen secara langsung meningkatkan suhu permukaan hingga 3°C dan menurunkan indeks kualitas udara hingga 20 persen. Model prediktif mereka menunjukkan bahwa setiap pengurangan satu persen tutupan vegetasi dapat meningkatkan angka kematian terkait panas ekstrem dan penyakit pernapasan. Dengan kata lain, hilangnya RTH bukan sekadar degradasi lingkungan, melainkan peningkatan risiko kematian. Kita sedang memperpendek usia kolektif umat manusia di kota.
Kesenjangan Regulasi dan Inkonsistensi Tata Ruang
Masalah semakin pelik ketika regulasi tata ruang tidak ditegakkan secara konsisten. Standar RTH 30 persen sering kali hanya menjadi angka di atas kertas. Banyak proyek besar yang mendapat dispensasi dengan membayar kompensasi atau menyediakan “RTH pengganti” di lokasi yang tak berfungsi ekologis. Padahal, manfaat RTH bersifat lokal dan tersebar—tidak bisa diganti dengan lahan di tempat lain.
Sebuah taman kecil di pusat kota lebih penting bagi sirkulasi udara dan kesehatan warga daripada taman besar di pinggiran yang tak terjangkau publik. Namun kebijakan sering berpihak pada kepentingan investor, bukan keseimbangan ekologis.
Kita perlu mengubah paradigma pembangunan kota dari grey infrastructure menjadi green infrastructure. Pembangunan yang sejati bukanlah menumpuk beton, melainkan menanam kembali kehidupan. Pemerintah daerah harus menegakkan peraturan tata ruang yang melindungi RTH secara permanen.
Lahan hijau yang sudah ada harus disertifikasi sebagai wilayah konservasi kota yang tidak dapat diubah peruntukannya. Setiap pengalihfungsian lahan hijau wajib diganti dengan rasio minimal tiga kali lipat dari luas yang hilang, dan penempatannya harus strategis dalam sistem ekologi kota, bukan di lokasi terpencil yang sekadar memenuhi syarat administratif.
Keterbatasan lahan juga bukan alasan. Solusinya ada dalam inovasi berbasis alam atau nature-based solutions. Atap gedung bisa ditanami kebun (green roof), dinding beton bisa menjadi taman vertikal, dan jalan raya bisa dihijaukan dengan pohon besar yang menciptakan koridor ekologis. Kota seperti Singapura telah membuktikan bahwa arsitektur modern dan ekologi bisa berpadu. Mereka menanam pepohonan bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai strategi mitigasi iklim. Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hal yang sama, hanya butuh kemauan politik dan kesadaran publik.
Di luar pemerintah, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting. Kepemilikan sosial terhadap RTH perlu dibangun melalui program taman komunitas (community garden) atau kebun kota. Ketika warga merasa memiliki taman di lingkungannya, mereka akan menjaganya dari perusakan. Taman bukan lagi milik pemerintah, melainkan milik bersama. Dalam hal ini, ruang hijau bukan hanya menumbuhkan tanaman, tetapi juga solidaritas sosial. Ia menghubungkan kembali manusia dengan tanah, dengan sesama, dan dengan rasa tanggung jawab terhadap tempat tinggalnya.
RTH adalah Masa Depan Kota
Pada akhirnya, mempertahankan RTH bukan sekadar urusan estetika, tetapi perjuangan untuk keberlanjutan hidup. Kota yang kehilangan hijaunya akan kehilangan kemanusiaannya. Dalam tubuh urban yang kian keras dan bising, warna hijau adalah simbol harapan, keseimbangan, dan keberlanjutan. RTH adalah ventilator kehidupan yang membuat kita bisa bernapas di tengah sesak peradaban modern. Mengabaikannya berarti menutup jalan bagi masa depan yang layak huni.
PBB memperingatkan bahwa pada tahun 2050, sebagian besar manusia akan hidup di kota. Maka, pertempuran terbesar abad ini tidak akan terjadi di medan perang, melainkan di perencanaan kota—antara beton dan pepohonan, antara keserakahan dan keberlanjutan. Kota yang maju bukanlah yang memiliki gedung tertinggi, melainkan yang memberi ruang bernapas bagi manusia dan ekosistemnya. Di situlah ukuran peradaban sesungguhnya.
Pilihan kini ada di tangan kita. Apa terus membangun kota yang panas, sesak, dan sakit-sakitan, atau menanam kembali masa depan melalui ruang terbuka hijau yang menjadi jantung keberlanjutan. Di antara hiruk pikuk mesin dan gedung, masa depan yang hijau mungkin tampak utopis. Namun tanpa utopia hijau itu, kita hanya akan mewariskan kepada anak cucu sebuah kota yang kehilangan napasnya. Dan pada hari itu, mungkin baru kita sadari bahwa yang hilang bukan sekadar pepohonan, melainkan kehidupan itu sendiri.
***
*) Oleh : Agum Muladi, Mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?