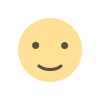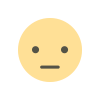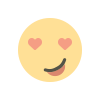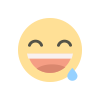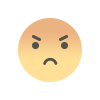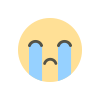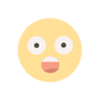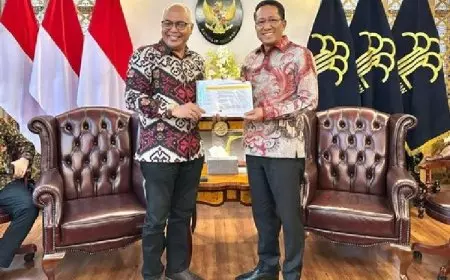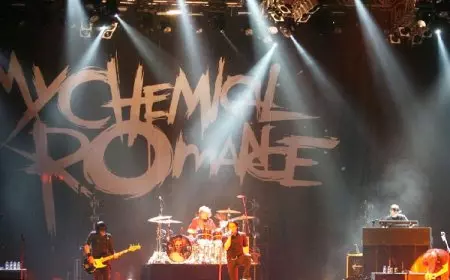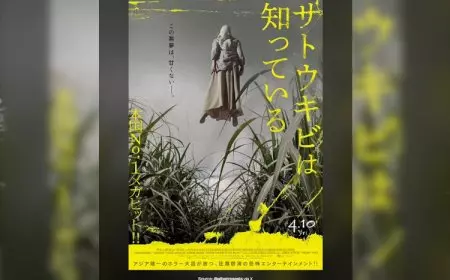Dari Langkah ke Makna: Cara Baru Mengajar Matematika
Sebagai guru dan pendidik matematika, saya sering melihat kegembiraan sesaat ketika murid berhasil menekan tombol kalkulator, menyalin langkah, lalu mendapatkan jawaban yang “betul”.

MALANG Sebagai guru dan pendidik matematika, saya sering melihat kegembiraan sesaat ketika murid berhasil menekan tombol kalkulator, menyalin langkah, lalu mendapatkan jawaban yang “betul”. Dua minggu kemudian, langkah itu hilang seperti catatan di papan yang terhapus cepat-cepat. Di sinilah bedanya hafal-prosedur dan paham-relasi.
Skemp dalam bukunya The Psychology of Learning Mathematics membedakan pemahaman instrumental—mengetahui langkah—dengan pemahaman relasional—mengerti jaringan alasan yang membuat langkah itu bekerja. Jika tujuan kita bukan hanya lulus ulangan melainkan membentuk ingatan yang tahan waktu dan bisa dipakai di situasi baru, maka relasional lah jalannya.
Mari turun ke kelas. Saat membahas luas segitiga, saya bisa saja menulis dan memberi lima belas soal latihan. Kelas akan sunyi, kertas terisi, dan nilai tampak rapi. Namun ketika bentuk segitiga dimiringkan, atau titik puncaknya digeser di aplikasi, banyak yang mendadak ragu.
Sebaliknya, ketika saya mengajak mereka “menciptakan” rumus—menempelkan segitiga pada persegi panjang untuk melihat “setengah”, lalu menunjukkan melalui shear bahwa bentuk berubah tetapi luas tetap—murid mulai berbicara dengan kosakata berbeda: tetap, berubah, alasan.
Ausubel dalam The Psychology of Meaningful Verbal Learning menegaskan bahwa informasi baru akan melekat kuat saat ia terpaut pada struktur kognitif yang sudah bermakna. Dengan kata lain, ketika rumus disangkutkan pada cerita yang bisa mereka lihat dan jelaskan, memori tak berjalan sendirian.
Kekuatan relasional bukan hanya daya simpan, tetapi juga daya sebar. Ketika murid memahami mengapa luas segitiga “setengah dari persegi panjang”, mereka lebih siap menghadapi konteks yang belum pernah dilihat. Bransford dalam How People Learn menunjukkan bahwa pemahaman yang terhubung memfasilitasi transfer: murid mampu mengenali pola yang sama di situasi berbeda. Ini menjawab keluhan klasik “Pak, bentuknya beda…”. Begitu mereka memiliki peta relasi, jalan memotong hutan masalah menjadi mungkin, bukan kebetulan.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Tentu, membangun relasional tak identik dengan membuat pelajaran berat. Triknya justru pada orkestrasi pengalaman kecil yang memaksa otak “mengikat” informasi. Bjork dalam Desirable Difficulties menjelaskan bahwa kesulitan yang dirancang—misalnya harus mengambil jeda sejenak untuk menjelaskan, atau menyelesaikan satu soal dengan dua cara—mungkin terasa lebih lambat sekarang, tetapi menumbuhkan jejak memori yang lebih kuat untuk nanti. Saya sering mengundang kelas untuk berhenti setelah menemukan jawaban, lalu bertanya, “Jika titiknya saya geser, apa yang tetap?” Biasanya ada yang berseloroh, “Pak, yang tetap cuma jadwal piket.” Kami tertawa sebentar, lalu kembali ke inti: invariansi apa yang menyatukan berbagai situasi?
Bahasa adalah jembatan antara relasi dan ingatan. Sfard dalam Thinking as Communicating memandang belajar matematika sebagai masuk ke diskursus baru: kata-kata yang kita gunakan membentuk objek yang kita pikirkan. Itulah mengapa saya mengganti instruksi “gambar bangun berikut” menjadi “bangunlah bangun berikut”—pergeseran kecil dari meniru ke mencipta. Saat murid menamai apa yang tetap dan apa yang berubah, mereka sedang menenun memori dengan benang bahasa; bukti yang mereka ucapkan menguatkan jejak yang mereka simpan.
Bagaimana memulainya tanpa merombak kurikulum? Besok pagi, buka pelajaran dengan satu momen “dua cara, satu jawaban”. Ambil satu soal inti—luas, keliling, atau kemiringan garis—dan minta murid menyelesaikannya lewat dua representasi berbeda, lalu tuliskan satu kalimat mengapa keduanya sah. Di tengah sesi, sisipkan kontra-contoh mungil untuk menguji definisi: misalnya, apakah bangun ini masih segitiga jika salah satu sisinya melengkung? Biarkan kelas berdebat singkat sebelum Anda menuntun ke definisi yang lebih presisi. Menjelang akhir, ajak refleksi bahasa selama dua menit: istilah mana yang paling membantu hari ini dan mengapa; aktivitas kecil ini menutup pelajaran dengan simpul makna yang lebih rapat.
Ada yang khawatir “cara begini makan waktu”. Kekhawatiran yang wajar. Tetapi pengalaman saya menunjukkan bahwa dua atau tiga momen relasional dalam satu jam pelajaran justru menghemat waktu esok lusa. Ketika konsep tertambat pada alasan, kebutuhan remedi menurun, dan sesi “mengulang lagi dari nol” makin jarang. Selain itu, suasana kelas menjadi lebih hidup. Murid merasa gagasan mereka penting, bukan sekadar langkah yang diuji kunci jawaban. Kalau sesekali kita menyelipkan candaan—“Tenang, integral tidak akan mengintimidasi; dia hanya ingin area di bawah kurva diakui keberadaannya”—itu bukan bumbu kosong, melainkan strategi menjaga energi bernalar.
Freudenthal dalam Mathematics as an Educational Task mengingatkan kita untuk memanggil konsep lewat fenomena yang masuk akal. Di tengah keterbatasan waktu dan tekanan asesmen, undangan sederhana pada fenomena—perputaran jarum jam untuk sudut, ubah-ubah titik untuk luas, tarik-geser grafik untuk turunan—sudah cukup membukakan pintu bagi relasi. Ketika murid menemukan “mengapa”-nya, ingatan tidak lagi sekadar gudang langkah, melainkan jaringan makna yang siap dipakai.
“Kita mengajar bukan agar murid mengingat segalanya, tetapi agar yang mereka ingat berguna ketika dunia meminta penjelasan. Prosedur membuat mereka sampai di jawaban hari ini, relasi menuntun mereka memahami pertanyaan hari esok. Dan kelas matematika—dengan humor yang tepat, bahasa yang jernih, dan fenomena yang mengundang—adalah tempat terbaik untuk melatih keduanya”. ***
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*) Penulis: Isbadar Nursit, S.Pd., M.Pd, Dosen Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?