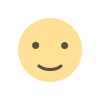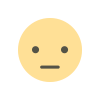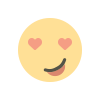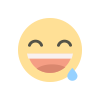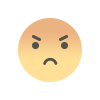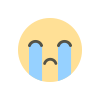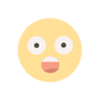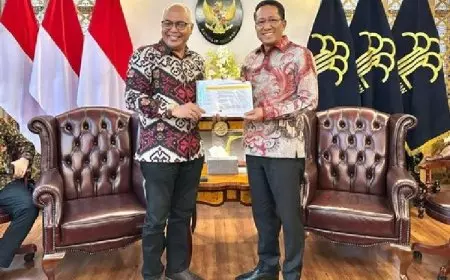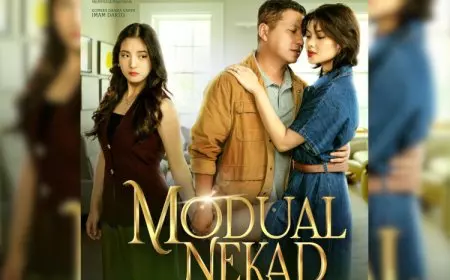Gestun dan Krisis Kepercayaan dalam Sistem Pembayaran Digital
Gestun—atau gesek tunai—sebagai praktik ilegal dalam sistem pembayaran digital kini bukan lagi sekadar pelanggaran regulasi

Gestun—atau gesek tunai—sebagai praktik ilegal dalam sistem pembayaran digital kini bukan lagi sekadar pelanggaran regulasi, melainkan sudah menjadi petunjuk nyata dari krisis kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital Indonesia. Ketika masyarakat mulai meragukan tidak hanya keamanan produknya, tapi juga legitimasi penyelenggaranya, implikasinya meluas: dari risiko individual hingga ke stabilitas sistem pembayaran dan keuangan nasional.
Gestun dilarang jelas oleh Bank Indonesia dan OJK. Menurut aturan PBI No. 11/11/ PBI/2009 dan amandemennya, serta berbagai himbauan dari bank, gestun adalah penyalahgunaan kartu kredit: semacam transaksi fiktif di merchant sehingga pemegang kartu mendapatkan uang tunai secara ilegal. sisi hukum, aspek larangan sudah kuat; namun praktiknya terus terjadi dan berkembang, yang menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup jika tidak diikuti pengawasan dan kepatuhan di lapangan.
Contoh paling segar adalah kasus gestun fiktif di Jambi—seorang wanita berinisial WW, yang juga istri seorang anggota kepolisian, menawarkan jasa gestun dengan iming-iming cashback besar (30-47 %) melalui toko online fiktif. Korban diminta “checkout” barang yang tidak ada, lalu dijanjikan keuntungan setelah beberapa hari. Akibatnya, 32 orang menjadi korban dengan total kerugian sekitar Rp 4,8 miliar. Kasus ini menggambarkan dua hal: betapa praktik gestun telah terorganisir dan melibatkan institusi informal (merchant online, media sosial), dan betapa klaim keuntungan cepat menjadi daya tarik kuat meskipun tanpa kejelasan legal maupun teknis.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Dalam konteks ini, krisis kepercayaan muncul karena: pertama, konsumen seringkali tidak dapat membedakan mana praktik digital yang legal dan mana yang ilegal; kedua, kerugian yang dialami antara lain bukan hanya materiil—uang hilang, data pribadi bocor, identitas disalahgunakan, utang fiktif muncul—but juga psikologis: rasa takut dan sinisme terhadap produk keuangan digital. Ketiga, institusi pengawas walau aktif mengingatkan dan mengedukasi, tapi respons terhadap pelanggaran sering lambat dan sulit menjangkau praktik-praktik gestun bersemayam di media sosial atau platform online yang “longgar” pengawasannya. Kasus gestun di media sosial yang akun-akunnya diberi label “verified” atau “blue tick” misalnya, menunjukkan betapa penipuan bisa memperoleh legitimasi visual bahkan sebelum adanya investigasi formal.
Dari sisi regulasi dan institusi, ada pula isu bahwa sistem pengawasan dan sanksi masih belum efektif mencegah penyelenggaraan gestun. Bank dan OJK sudah memperingatkan bahwa nasabah yang terlibat gestun tidak akan mendapatkan perlindungan, bahwa data pribadi bisa disalahgunakan, dan bahwa gestun membuka pintu bagi pencucian uang. Tapi kenyataannya pelaku tetap beroperasi, banyak korban tidak melapor, dan banyak layanan gestun di luar jangkauan regulasi langsung. Kesenjangan antara hukum/regulasi di atas kertas dan realita lapangan semakin terlihat jelas.
Ketika kepercayaan melemah, efeknya berbahaya: masyarakat bisa enggan menggunakan layanan digital yang sebenarnya sah dan berguna—misalnya paylater terpercaya, kartu kredit resmi, dompet digital (e-wallet). Mereka bisa curiga semua tawaran mengandung risiko hidden fee, penipuan, atau kerugian data pribadi. Akhirnya inklusi keuangan digital yang menjadi salah satu tujuan besar transformasi ekonomi digital bisa terganggu. Apalagi ketika publik menyaksikan bahwa ada oknum terkait institusi keamanan yang terlibat dalam kasus penipuan seperti di Jambi, kepercayaan terhadap regulator dan penegak hukum itu sendiri ikut tergerus.
Untuk memperbaiki keadaan, beberapa langkah harus ditempuh secara simultan. Penguatan regulasi tidak cukup; penegakan hukum harus lebih cepat dan transparan, publik harus diberikan edukasi yang konkret tentang risiko digital, dan kelembagaan pengawas harus mampu mengawasi tidak hanya formalitas tapi juga praktik-praktik di ranah informal dan sosial media. Teknologi seperti sistem deteksi penipuan otomatis, identitas digital yang terverifikasi, dan track record merchant bisa menjadi bagian dari solusi—namun hanya jika penyelenggara fintech, platform online, perbankan, dan regulator bekerjasama dan memiliki integritas.
Tentu, tanpa kepercayaan masyarakat, seluruh arsitektur pembayaran digital bisa runtuh. Mari kita ingat bahwa satu transaksi fiktif, satu penipuan gestun, bukan hanya merugikan korban secara finansial, tapi merusak kepercayaan umum—dan memulihkannya jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak awal.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?