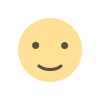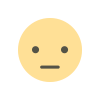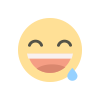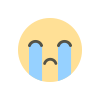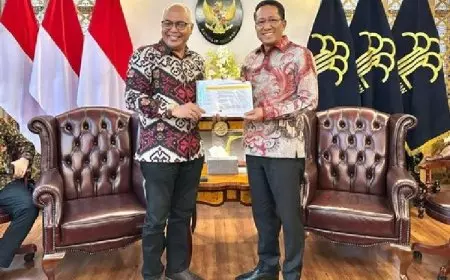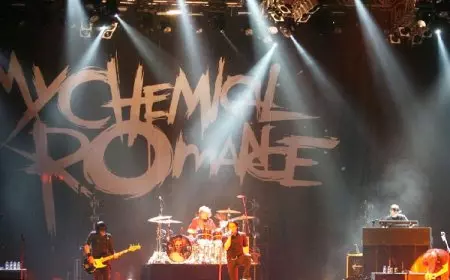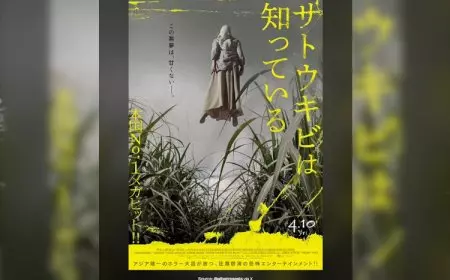UWG Malang Gelar Diskusi Kolaboratif, Saat Perempuan Adat dan Alam Bicara Melawan Kekerasan
Suasana hangat dan penuh dialog terasa di kafe Kantin Kampus III Universitas Widya Gama (UWG) Malang

MALANG Suasana hangat dan penuh dialog terasa di kafe Kantin Kampus III Universitas Widya Gama (UWG) Malang, Jumat (19/12/2025).
Diskusi Kolaboratif MAMA ALETA FUND, FORMA PHM Fakultas Hukum UWG, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang digelar untuk mengajak publik berbicara lebih dekat tentang kekerasan terhadap perempuan, perusakan alam, dan perlawanan berbasis budaya adat.
Kegiatan ini diinisiasi sekaligus dimoderatori oleh Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH., MH., dosen Fakultas Hukum UWG Malang yang dikenal sebagai pakar hukum lingkungan dan hukum adat. Diskusi diikuti oleh mahasiswa UWG, akademisi, jurnalis AJI Malang, serta mahasiswa FH UWG yang tergabung dalam FORMA PHM (Forum Mahasiswa Pengkaji Hukum untuk Masyarakat).
Diskusi tersebut menjadi bagian dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP)—kampanye global yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember, untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Forum ini juga menyoroti keterkaitan erat antara kekerasan berbasis gender dengan kerusakan lingkungan dan krisis iklim, yang dampaknya kerap dirasakan paling berat oleh perempuan.
FH UWG Dorong Academic Judivism
Dalam pemaparannya, Dr. Purnawan Dwikora Negara menekankan pentingnya peran dosen untuk menjalankan academic judivism, yakni keberpihakan akademik pada nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Dosen harus melakukan academic judivism. Fakultas Hukum UWG hadir sebagai bentuk pembelaan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa FH UWG agar mengetahui dan peduli,” tegasnya. Menurut Purnawan, sebagai dosen hukum adat, momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Alam sangat tepat untuk menghadirkan langsung penulis buku dan narasi perjuangan perempuan adat agar mahasiswa memahami hukum sebagai realitas hidup, bukan sekadar teks.

Paparan Penulis Buku: Perjuangan Perempuan Tidak Pernah Gratis
Salah satu sesi penting dalam diskusi adalah pemaparan dari Siti Maimunah, dosen Universitas Indonesia sekaligus penulis buku Senjata Kami adalah Upacara Adat. Dalam paparannya, Siti menegaskan bahwa tidak ada satu pun perjuangan perempuan di dunia yang diperoleh secara gratis.
“Perjuangan perempuan selalu melalui jalan panjang dan berat. Dari tahun 1908 hingga 2018, semua capaian perempuan harus diperjuangkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa perjuangan perempuan tidak pernah berlangsung di ruang kosong. Perempuan selalu membutuhkan mitra dan solidaritas, karena sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial selalu melibatkan peran perempuan, termasuk dalam konteks ekonomi dan politik global. Siti mencontohkan bagaimana pada masa Perang Dunia II, hampir seluruh aktivitas industri dan perusahaan bergantung pada tenaga perempuan. Namun setelah perang usai, pasar dialihkan—alat-alat perang berubah menjadi alat-alat dapur, dan perempuan kembali didorong ke ruang domestik.
Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan Revolusi Hijau tahun 1960-an, yang menurutnya tidak hanya berdampak pada sistem pertanian, tetapi juga memperdalam ketimpangan dan eksploitasi terhadap alam serta perempuan. Dari sinilah buku Senjata Kami adalah Upacara Adat menemukan relevansinya.
Ekofeminisme: Alam dan Perempuan Sama-sama Dieksploitasi
Siti Maimunah menegaskan bahwa buku ini berangkat dari perspektif ekofeminisme, yang melihat bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap alam memiliki hubungan langsung dengan kekerasan terhadap perempuan. Ia mencontohkan ungkapan perempuan Papua yang menyebut gunung sebagai “nemangkuwi”—ibu yang mengandung dan memberi kehidupan. Ketika alam dirusak, maka perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

Struktur Buku: Permisi, Nompah, dan Pamit
Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa buku Senjata Kami adalah Upacara Adat disusun dengan struktur ungkapan yang khas dan sarat makna budaya, yaitu:
-
Permisi — sebagai pembuka, bentuk penghormatan sebelum memasuki kisah dan ruang hidup perempuan adat.
-
Nompah — napak tilas perjalanan hidup lima Nausus. Bagian ini merupakan hasil dari proses panen pengetahuan, yang disusun melalui tiga tahapan penting, menggali ingatan, tubuh, dan laku hidup perempuan adat.
-
Pamit — sebagai penutup, sekaligus penegasan bahwa perjuangan belum selesai dan harus diteruskan.
Dalam proses Nompah, Siti juga mengenalkan konsep Naketi, yakni pembacaan kritis tentang hubungan antara alam, kapitalisme, dan perempuan. Naketi menjadi ruang refleksi bahwa kerusakan ekologis tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan menyingkirkan perempuan dari pengambilan keputusan.
Perempuan Adat sebagai Penjaga Kehidupan
Buku ini merekam suara lima Nausus, perempuan adat yang berdiri di garda depan perjuangan lingkungan: Mama Aleta Baun dari Mollo, Maria Loretha dari Adonara, Jull Takaliuang dari Pulau Sangihe, Mardiana penjaga hutan Gunung Kerasik, serta Gunarti dari Pegunungan Kendeng. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa upacara adat, doa, dan simbol tubuh–alam menjadi senjata kultural dalam mempertahankan kehidupan.
Sebagaimana ditegaskan dalam pengantar buku oleh Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN):
“Selama mereka masih berdiri, Masyarakat Adat belum kalah. Dan tidak akan pernah sendiri.”
Melalui diskusi kolaboratif ini, UWG Malang menegaskan perannya sebagai ruang akademik yang berpihak pada keadilan gender dan keadilan ekologis, serta mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa hukum, perjuangan perempuan, dan penyelamatan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. (*)
Apa Reaksi Anda?