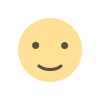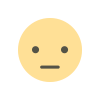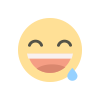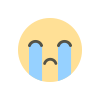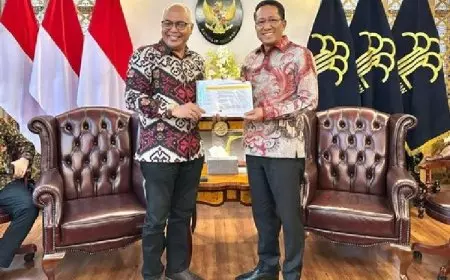Metafora Politik dan Imajinasi Kekuasaan Amerika
John Rambo bukan sekadar tokoh film aksi, melainkan produk budaya populer yang merepresentasikan imajinasi kekuasaan Amerika Serikat.

PROBOLINGGO John Rambo bukan sekadar tokoh film aksi, melainkan produk budaya populer yang merepresentasikan imajinasi kekuasaan Amerika Serikat. Sejak debutnya pada Oktober 1982, figur Rambo memanifestasikan simbol maskulinitas ekstrem, kekerasan yang dilegitimasi, dan keyakinan akan kemenangan moral di tengah dunia yang digambarkan penuh ancaman.
Konflik disederhanakan, musuh dipersonifikasikan hitam-putih, dan kekerasan tampil bukan sebagai problem etis, melainkan sebagai solusi yang dianggap sah dan perlu.
Film dapat dibaca sebagai teks budaya melalui teori mitos modern Roland Barthes dan teori representasi Stuart Hall. Barthes, dalam Mythologies (1957), menjelaskan bahwa produk budaya populer bekerja sebagai mitos modern yang menaturalisasi ideologi, menjadikan kepentingan historis dan politis tampak alamiah dan tak terbantahkan.
Stuart Hall, dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997), menegaskan bahwa representasi bukanlah cermin realitas yang bersifat mimesis (peniruan), melainkan sebuah praktik penandaan (signifying practice) yang mengonstruksi makna melalui wacana dan relasi kuasa.
Rambo, melalui kerangka pemaknaan tersebut, berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai representasi ideologis yang membentuk cara pandang tentang musuh, legitimasi kekerasan, dan posisi Amerika Serikat dalam tatanan global.
Sebagai mitos kultural, Rambo lahir dari konteks sejarah trauma kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam serta krisis kepercayaan terhadap institusi negara pada akhir Perang Dingin. Serial film ini menawarkan kompensasi simbolik atas kegagalan sejarah tersebut; kekalahan di Vietnam tidak diakui secara terbuka, melainkan disublimasikan menjadi kemenangan fiktif melalui individu yang mampu melakukan apa yang diplomasi dan institusi resmi tidak sanggup capai: menang, membalas, dan memulihkan harga diri nasional.
Logika mitos budaya modern mengubah sejarah menyakitkan; alih-alih dihadapi jujur, narasi tersebut dipoles menjadi cerita alamiah pembenaran tatanan kekuasaan. Fakta kekalahan, kompleksitas politik, maupun penderitaan korban lenyap dari kesadaran publik.
Posisi mereka digantikan narasi sederhana: pahlawan, musuh absolut, serta kemenangan tak terbantahkan. Melalui mekanisme ini, film Rambo melampaui fungsi hiburan yang bekerja sebagai mitos penenang kecemasan kolektif sekaligus normalisasi kekerasan sebagai tindakan wajar.
Mitologi ini tidak berhenti pada sinema, melainkan meresap ke dalam imajinasi politik dan membentuk cara publik memahami peran negaranya di panggung global. Ide tentang pahlawan tunggal dan musuh absolut menjadi kerangka berpikir yang terus direproduksi dalam wacana kebijakan luar negeri serta retorika keamanan nasional.
Budaya populer serta politik nyata saling bertaut sekaligus memperkuat. Konteks demikian menjadikan Rambo pintu masuk krusial guna membedah mitologi kekuasaan Amerika secara kritis. Penelusuran setiap fase filmnya sejak era Perang Vietnam hingga paranoia keamanan domestik menyingkap proses pembangunan imajinasi kekuasaan serta penyesuaiannya terhadap tuntutan zaman.
Figur-figur politik nyata pun dapat dibaca dalam kerangka ini, di mana kepemimpinan dan legitimasi demokratis tidak berdiri sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai ekspresi konkret dari imajinasi kekuasaan yang telah lama hidup dalam budaya mereka.
Rambo-isme dalam Politik
Gambaran aksi heroik yang menjadi kebanggaan Amerika ini terpotret jelas dalam First Blood (1982) yang diadaptasi dari novel David Morrell (1972). Sebagai veteran yang dikhianati oleh sistem dan diperlakukan kasar oleh aparat lokal, pelarian Rambo memicu perburuan besar-besaran yang menampilkan kekerasan sebagai simbol perlawanan individu terhadap otoritas yang sewenang-wenang.
Paralel dengan simbolisme tersebut, dalam kehidupan nyata terdapat sejumlah peristiwa yang memperlihatkan pola serupa: individu bersenjata yang berkonflik dengan aparat negara, namun justru memperoleh glorifikasi dari sebagian publik.
Kasus Randy Weaver dalam peristiwa Ruby Ridge (1992), misalnya, sering disebut sebagai “Rambo versi nyata”. Weaver dipandang oleh sebagian kalangan bukan sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai korban represi negara federal sebuah narasi “warga biasa versus negara bersenjata” yang menguat di kalangan libertarian.
Pola ini berlanjut dengan kompleksitas yang lebih ekstrem dalam tragedi Waco Siege (1993). Tindakan aparat yang berujung maut justru memperkuat sentimen anti-negara, di mana negara tidak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman.
Sentimen perlawanan kolektif ini mencapai titik unik dalam kasus Cliven Bundy pada Bundy Standoff (2014). Saat itu, negara memilih mundur menghadapi perlawanan bersenjata warga sipil untuk menghindari pertumpahan darah, yang kemudian membuat Bundy dipuja sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap federalisme.
Fenomena ini muncul kembali dalam wajah yang berbeda melalui Kyle Rittenhouse (2020). Dalam situasi kekacauan sipil, Rittenhouse dipersepsikan oleh para pendukungnya sebagai individu yang “menggantikan fungsi negara” ketika aparat dianggap tidak efektif, sehingga ia memperoleh legitimasi moral sebagai pembela diri.
Budaya politik Amerika menyediakan ruang simbolik identik mitologi Rambo melalui narasi individu tunggal bersenjata yang memosisikan diri sebagai korban sistem guna melegitimasi kekerasan defensif terhadap personifikasi negara kasar. Tradisi pemuliaan individu melawan kesewenang-wenangan ini menjadikan Rambo bukan sekadar film fiksi, melainkan cermin imajinasi politik sekaligus kunci pemahaman atas simpati publik terhadap figur seperti Weaver, Bundy, atau Rittenhouse.
Selama imajinasi "pahlawan terzalimi" tetap terpelihara, batas penegakan hukum serta aksi main hakim sendiri dalam demokrasi modern terus menjadi medan pertempuran persepsi kabur sebuah ruang abu-abu di mana pelanggaran hukum dapat dipandang sebagai kepahlawanan moral, sementara ketertiban negara justru dianggap sebagai represi. Imajinasi serupa pula yang menjadi landasan gaya kepemimpinan politik kontemporer dengan kecenderungan unilateral serta konfrontatif terhadap tatanan global.
***
*) Oleh : Didik P. Wicaksono, Penulis adalah Pendengar Cerita Amerika Serikat.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?