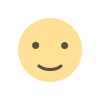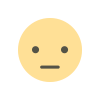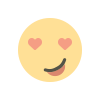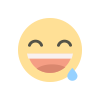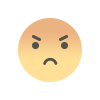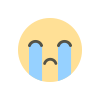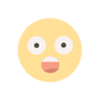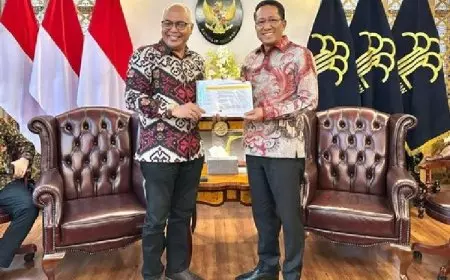Rasionalitas Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia
Perkawinan anak —yang didefinisikan sebagai menikah di bawah usia 19 tahun— masih menjadi persoalan mendesak dan kompleks di Indonesia.

Perkawinan anak —yang didefinisikan sebagai menikah di bawah usia 19 tahun— masih menjadi persoalan mendesak dan kompleks di Indonesia. Meskipun regulasi telah diperbarui dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman mengadili permohonan dispensasi, tantangan di lapangan tetap besar.
Persoalan kuncinya tidak hanya terletak pada keberadaan undang-undang, tetapi pada implementasi dispensasi kawin itu sendiri dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berlapis. Secara argumentatif, kita perlu mengkritisi apakah dispensasi kawin benar-benar rasional sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak, ataukah justru telah berubah menjadi pintu belakang untuk melegalkan praktik yang pada dasarnya merugikan masa depan anak.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin justru semakin marak. Sebagai contoh, di Bojonegoro, Jawa Timur, permohonan dispensasi dilaporkan mengalami kenaikan sekitar 200% sejak tahun 2019. Sementara itu, di Indramayu, ratusan kasus tercatat setiap tahunnya: 654 kasus pada 2021, 574 pada 2022, 514 pada 2023, dan telah mencapai 332 kasus hingga awal Desember 2024.
Data nasional tahun 2020 juga mencatat lonjakan signifikan, dari sekitar 23.386 dispensasi pada 2019 menjadi 64.487 pada 2020. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi belum secara efektif menekan angka permohonan perkawinan di bawah umur.
Menyoroti rasionalitas dispensasi, kritik utama muncul terhadap longgarnya interpretasi atas alasan "keadaan mendesak" yang dipersyaratkan oleh Perma 5/2019. Dalam praktiknya, apa yang dianggap "mendesak" seringkali tidak jelas, subjektif, dan tidak konsisten.
Banyak permohonan dispensasi diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan norma sosial atau agama, atau sekadar alasan "cinta" antara pasangan muda. Misalnya, sebuah penelitian di Indramayu terhadap 50 putusan dispensasi menemukan bahwa 88% di antaranya (44 kasus) dilatarbelakangi oleh kehamilan.
Yang lebih memprihatinkan, kehamilan ini seringkali dibuktikan dengan surat keterangan hamil palsu hanya untuk mempermudah pengajuan dispensasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa klausul "keadaan mendesak" telah disalahgunakan menjadi tameng untuk melegitimasi perkawinan anak.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Di sisi lain, prinsip utama dispensasi yang seharusnya memastikan "keputusan terbaik bagi anak" seringkali terabaikan. Idealnya, hakim harus mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, kesiapan mental dan fisik, serta jaminan perlindungan dari kekerasan. Namun, penelitian Plan Indonesia di Sukabumi dan Lombok Barat mengungkap bahwa hakim jarang memverifikasi atau memastikan pemenuhan hak-hak tersebut pasca-pernikahan. Tidak ada mekanisme monitoring yang sistematis, sehingga banyak anak, terutama perempuan, yang terpaksa putus sekolah dan aspek kesehatannya tidak terpantau.
Akar persoalan ini juga erat kaitannya dengan faktor struktural seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Banyak pemohon dispensasi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan akses informasi terbatas. Di Bojonegoro, banyak pemohon hanya berpendidikan SD atau SMP, sementara di Indramayu, calon istri umumnya berpendidikan SMP dan tidak bekerja, sedangkan calon suami memiliki penghasilan yang tidak stabil. Dalam konteks ini, dispensasi kawin bukannya menjadi solusi, melainkan justru memperkuat siklus ketidaksetaraan. Anak-anak dari keluarga miskin semakin rentan terdorong ke dalam perkawinan dini karena minimnya dukungan sosial dan ekonomi.
Implikasi negatif jangka panjang dari perkawinan anak ini sangat serius.
Pertama, dari segi pendidikan, perkawinan di bawah umur hampir selalu mengakibatkan putusnya sekolah anak perempuan, yang pada akhirnya membatasi potensi ekonomi mereka di masa depan.
Kedua, dari aspek kesehatan, anak yang menikah dan hamil dalam usia muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, malnutrisi, serta meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
Ketiga, kombinasi dari pendidikan yang rendah dan kesehatan yang buruk akan memicu kemiskinan antar generasi, di mana keluarga yang terbentuk dari perkawinan anak cenderung terus terperangkap dalam kesulitan ekonomi.
Lebih jauh, dispensasi kawin juga berpotensi menimbulkan konflik regulatif dan melemahkan perlindungan hukum bagi anak. Mekanisme ini dapat menjadi celah untuk melegalkan kekerasan seksual terhadap anak, di mana kasus kehamilan yang seharusnya diusut di bawah UU Perlindungan Anak atau UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) justru "diselesaikan" melalui pernikahan. Alih-alih melindungi korban, dispensasi dapat mengaburkan pertanggungjawaban hukum pelaku.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Beberapa contoh kasus nyata memperkuat analisis ini. Di Bojonegoro, Pengadilan Agama setempat menerima 435 permohonan dispensasi hingga November 2023, dengan mayoritas pemohon berpendidikan rendah. Yang memprihatinkan, sekitar 50 pasangan yang dispensasinya dikabulkan justru bercerai dalam waktu kurang dari setahun, menunjukkan ketidaksiapan mereka membina rumah tangga.
Di Indramayu, selain tingginya angka dispensasi karena kehamilan (dan adanya penggunaan surat palsu), banyak juga kasus di mana anak "dipaksa" menikah karena tekanan sosial dan budaya dari orang tua. Sementara di Lombok Barat dan Sukabumi, tingkat pengabulan dispensasi mencapai 95-96%, namun implementasi "keputusan terbaik untuk anak" hanya sebatas retorika dalam putusan tanpa tindak lanjut pemantauan yang nyata.
Berdasarkan analisis kontekstual di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian memang memiliki potensi rasional jika digunakan dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan dengan pengawasan ketat. Namun, dalam praktiknya saat ini, dispensasi justru lebih sering menjadi celah hukum yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan.
Pertama, mendesak untuk memperjelas dan mempersempit definisi "keadaan mendesak" dalam Perma agar tidak ditafsirkan secara semena-mena oleh hakim, dengan menyertakan standar bukti yang objektif dan ketat.
Kedua, hakim yang menangani perkara dispensasi harus menjalani sertifikasi dan pelatihan khusus yang mendalam mengenai hak anak, psikologi perkembangan, kesetaraan gender, dan kesehatan reproduksi remaja.
Ketiga, harus ada mekanisme monitoring pasca-pemberian dispensasi untuk memastikan anak tetap dapat bersekolah, mengakses layanan kesehatan, dan terlindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, intervensi sosial dan ekonomi yang menyasar akar masalah—seperti bantuan pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, kampanye kesadaran masyarakat, dan program pencegahan kehamilan remaja—harus diintensifkan. Kelima, harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS mutlak diperlukan untuk menutup celah hukum yang dapat melemahkan perlindungan anak. ***
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Apa Reaksi Anda?